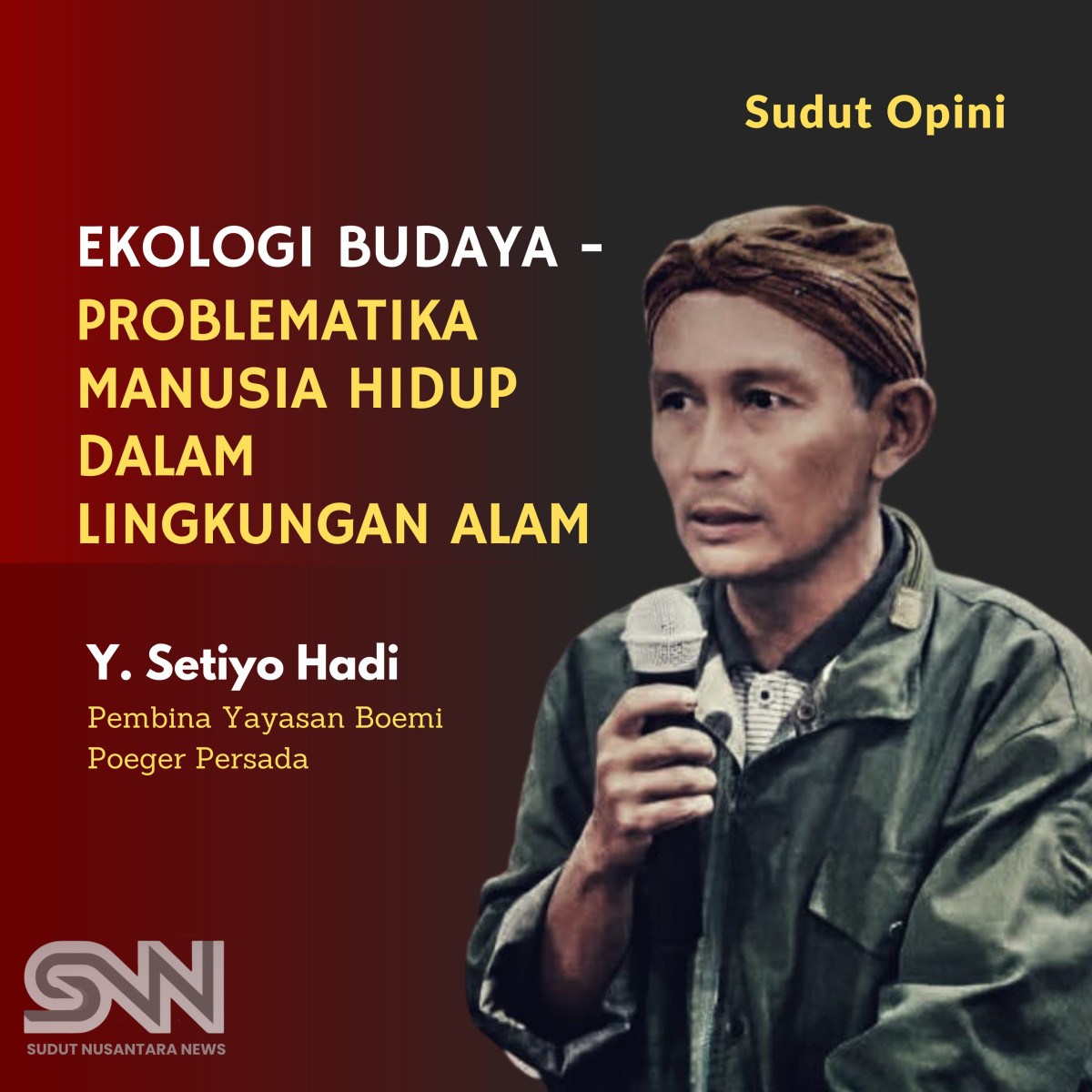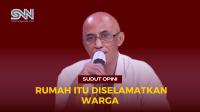“Alam memiliki caranya dalam kesinambungan keberadaanya yang dirasakan manusia sebagai berkah dan sekaligus sebagai bencana atau ancaman. Hal ini terekam dalam berbagai jejak peninggalan umat manusia dari masa ke masa yang sering dikenal sebagai kearifan lokal (local wisdom atau local genius). Setiap generasi manusia dari awalnya memiliki kearifan dalam menanggapi atau respon terhadap berkah dan ancaman dari cara-cara alam menjalani kesinambungan”.
Sarasehan Ekologi Budaya Hyang Argopuro merupakan langkah positif. Sarasehan Ekologi Budaya Hyang Argopuro, Kamis (27/2/2025), di aula R.Soemitro RRI Jember. Sarasehan ini dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat, pelaku seni budaya, pemerhati sejarah, mahasiswa dan pelajar dan awak media. Sarasehan Ekologi Budaya Hyang Argopuro menjadi bagian dari rangkaian Grebeg Budaya Kampung Jember 2025, menghadirkan empat pembicara ahli yang kompeten di bidangnya, yakni praktisi kecagarbudayaan, praktisi ekologi, Komisi B DPRD Jember, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
“Diskusi ini bertujuan untuk menggali dan memahami hubungan antara ekologi dan budaya di sekitar kawasan Argopuro bagian selatan, serta bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat Jember. Melalui perspektif masing- masing ahli, sarasehan ini menghasilkan rumusan yang berfokus pada perlindungan, pelestarian, dan pengembangan potensi ekologi budaya yang ada di daerah tersebut. Rumusan yang tercipta nantinya akan diajukan sebagai kebijakan publik, dengan harapan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih bijak dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya di Jember,” demikian ungkap Gunawan Trip , CO BalaiRW Institute yang juga aktif di Srawung Sastra, sebagai penyelenggara Sarasehan Ekologi Budaya Hyang Argopuro (rri.co.id)
Subyek pembahasan Ekologi Budaya sangatlah menarik dan perlu terus disosialisasikan dalam masyarakat, terutama bagi pemerintahan (legislatif maupun eksekutif). Garis besarnya ekologi budaya, yang bermula dari kajian ilmiah, merupakan kajian tentang hubungan antara budaya dan lingkungan, serta bagaimana budaya beradaptasi terhadap lingkungan.
Prinsip dasar ekologi budaya memberi penekanan pada keseimbangan antara manusia, budaya, dan lingkungan yang melibatkan persepsi manusia terhadap lingkungan. Ekologi Budaya berupaya memberikan wawasan kesadaran dampak manusia terhadap lingkungan, dan sebaliknya dengan melibatkan aksi dan teknologi dalam pengelolaan lingkungan.
Kesadaran yang ditata dalam kesadaran ekologi budaya membantu mewujudkan lingkungan masyarakat yang berkelanjutan, memelihara keseimbangan antara manusia dan alam, menjaga keberlanjutan bumi sebagai rumah manusia, menciptakan harmoni antara manusia dan lingkungan. Penerapan dari ekologi budaya dengan melestarikan kearifan lokal, meningkatkan kesadaran lingkungan, partisipasi masyarakat, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan.
Penekanan dari ekologi budaya adalah kearifan lokal (local wisdom, local genius) yang tercipta dalam suatu lingkungan alam sebagai bentuk respon manusia dalam menyikapi kondisi lingkungan alam dari masa ke masa.
Unsur-unsur pokok dalan pandangan adalah pola-pola perilaku (behavior patterns), yakni kerja (work), dan teknologi yang dipakai di dalam proses pengolahan atau pemanfaatan lingkungan. Pendekatan ekologi budaya diawali dengan “the process of work, its organizations, its cycle and rhyoms and its situational modalities”.
Fokus dari ekologi budaya terletak di analisis struktur sosial dan kebudayaan yang merujuk pada lingkungan alam tatkala alam mempengaruhi pola-pola tingkah laku atau organisasi kerja. Dalam hal ini, proses dan perilaku adaptif manusia menjadi perhatian dari ekologi budaya dengan menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana populasi manusia beradaptasi terhadap lingkungan sebagai bentuk dari kebudayaan.
Kebudayaan mempunyai peran sentral sebagai penentu pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan proses adaptasi dan keberlangsungan alam melalui kearifan lokal.
Kearifan lokal Tiga Ruang Dimensi
Pertama, ruang pengetahuan lokal. Setiap masyarakat dalam suatu lingkungan alam selalu mempunyai pengetahuan lokal yang diindikasikan dapat membedakan sumber daya alam yang dapat dikonsumsi atau dikembangbiakkan dengan dan sumber daya yang tidak dapat dikonsumsi atau berfungsi sebagai hiasan.
Kedua, ruang keterampilan lokal. Keterampilan lokal mempunyai fungsi sebagai kemampuan bertahan hidup (survival). Keterampilan lokal ini memperlihatkan fungsi kearifan lokal memberikan pengetahuan yang diturunkan secara turun temurun demi keberlangsungan generasi selanjutnya, baik menjadi peninggalan budaya benda (tangible heritage), maupun peninggalan budaya tak benda (intangible heritage).
Ketiga, ruang sumber daya lokal. Sumber daya lokal, umumnya, berupa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui yang terdapat di suatu daerah tertentu. Kearifan lokal dalam ruang ini dapat berwujud adat tradisi menjaga keberlangsungan alam dan lingkungannya aturan, biasanya berbentuk pantangan/larangan, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara arif dan bijak.
Ekologi Budaya dengan berfokus pada kearifan lokal menjadi guidance (petunjuk) dalam mengatur pola perilaku masyarakat. Keberadaan kearifan lokal cenderung lebih ekologis dibandingkan dengan masyarakat modern tanpa kearifan lokal dalam kehidupannya.
Setiyo Hadi
Pegiat Sejarah – Pembina Yayasan Boemi Poeger Persada
*) Konten di Sudut Opini merupakan tulisan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Sudut Nusantara News