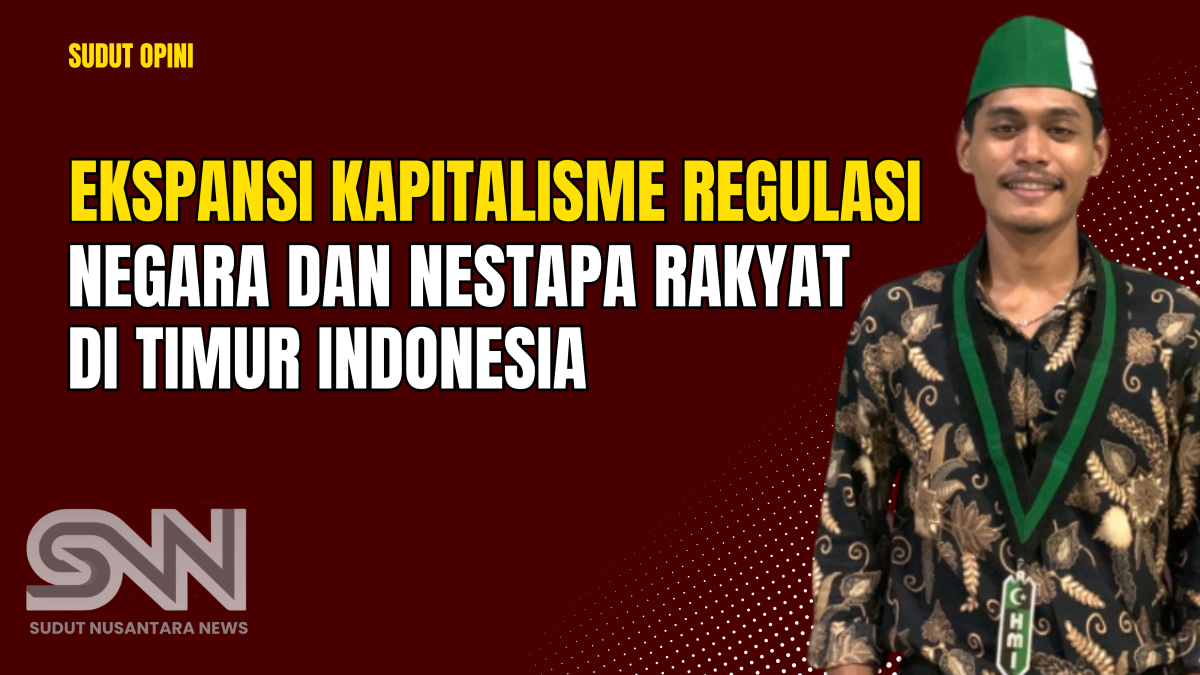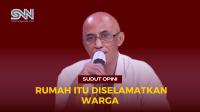Sudut Opini – Struktur masyarakat modern hari ini telah didominasi oleh kekuatan kapitalis yang menjadikan negara sebagai pintu utama dalam melanggengkan eksploitasi terhadap sumber daya manusia maupun kekayaan alam. Dalam skema ini, regulasi negara tidak lagi menjadi instrumen perlindungan rakyat, melainkan berfungsi sebagai alat legitimasi atas tindakan-tindakan tidak bermoral dari elite birokrasi dan pemilik modal. Ini merupakan bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap marwah demokrasi yang sejatinya meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.
Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan sejatinya menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan hidup yang mengedepankan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara. Abraham Lincoln bahkan menyebut demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”
Namun dalam praktik kapitalisme negara, demokrasi justru berubah menjadi kedok untuk menghancurkan konstitusi melalui regulasi yang melegalkan eksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan berkelanjutan. Pembangunan menjadi jargon manipulatif yang membungkus kerakusan elite dan pemilik modal dengan narasi kemajuan yang semu.
Salah satu alat utama eksploitasi ini adalah regulasi negara yang mendukung kepentingan modal, seperti: Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Minerba, yang memperpanjang otomatis izin tambang besar dan menarik kewenangan daerah ke pusat;
Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023), pembaruan dari UU Cipta Kerja 2020, memudahkan investasi dengan melonggarkan izin lingkungan (AMDAL), pemanfaatan lahan, dan pembukaan hutan adat;
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan percepatan proses AMDAL tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas;
UU Kehutanan dan UUPA 1960, yang masih digunakan untuk pemberian HGU dan konsesi hutan atas tanah adat.
Semua regulasi ini masih berlaku dan aktif digunakan hingga hari ini, menjadi dasar legal perampasan ruang hidup masyarakat adat dan eksploitasi ekologi di berbagai wilayah timur Indonesia.
Kawasan timur Indonesia, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat merupakan wilayah yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa: laut yang kaya akan ikan dan hasil laut lainnya, hutan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi, serta tambang emas, nikel, tembaga, dan minyak bumi. Namun ironi terjadi, masyarakat lokal yang hidup di atas kekayaan itu justru didera kemiskinan dan kelaparan berkepanjangan.
Berdasarkan data BPS 2024: Papua mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 26,03%, Papua Barat sebesar 20,41%, Maluku sebesar 16,23%, Maluku Utara sebesar 6,45%
Angka-angka ini menempatkan wilayah timur Indonesia sebagai provinsi-provinsi termiskin di Indonesia, jauh di atas rata-rata nasional. Ketimpangan ini mencerminkan distribusi hasil ekonomi yang tidak adil serta adanya ketidakadilan struktural dalam kebijakan pembangunan nasional.
Negara datang membawa regulasi yang berpihak pada kepentingan modal. Atas nama pembangunan, seluruh kekayaan alam diklaim sebagai milik negara, lalu diberikan konsesi kepada perusahaan besar, baik nasional maupun asing, untuk dieksploitasi. Di wilayah ini, terdapat sejumlah perusahaan besar yang menjadi simbol eksploitasi berkedok investasi:
Wilayah Maluku: PT Banda Permai Sakti: Perusahaan perikanan skala besar yang mengurangi akses nelayan tradisional di kawasan Seram dan sekitarnya.
Maluku Utara: PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP): Kawasan industri nikel di Halmahera yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.
PT Aneka Tambang (Antam): Aktif di wilayah tambang nikel Tanjung Buli.
PT Harita Nickel dan anak usahanya PT Trimegah Bangun Persada: Mengeksploitasi Pulau Obi yang sensitif secara ekologis dan budaya.
Papua Barat: PT Gag Nikel (anak usaha Antam): Beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat. Menimbulkan penolakan karena merusak kawasan pesisir dan pulau kecil.
PT Permata Putera Mandiri: Diduga kuat terlibat dalam alih fungsi hutan adat Sorong untuk kelapa sawit.
Di Raja Ampat, perusahaan resort dan layanan logistik seperti PT ASI Pudjiastuti Aviation berperan dalam mengakses kawasan eksklusif wisata, namun seringkali tidak melibatkan masyarakat lokal secara setara.
Papua: PT Freeport Indonesia: Raksasa tambang emas dan tembaga di Mimika. Dampaknya terhadap sungai, hutan, dan masyarakat adat masih menjadi isu utama.
PT Petrosea Tbk dan kontraktor tambang lain: Melakukan ekspansi proyek infrastruktur dan logistik pertambangan di Papua Tengah dan Pegunungan.
PT Korindo Group: Perusahaan sawit dan kayu besar yang menuai kecaman internasional karena merampas tanah adat dan menyebabkan deforestasi besar-besaran di Papua Selatan.
Praktik-praktik eksploitasi ini menyebabkan perampasan ruang hidup masyarakat adat, sekaligus menyulut konflik horizontal maupun vertikal. Mereka yang mempertahankan tanah dan hak hidupnya kerap dicap sebagai pemberontak dan berhadapan dengan tindakan represif dari aparat negara. Kekerasan atas nama pembangunan menjadi alat penaklukan baru.
Dampak ekologis pun tak kalah mengerikan: pencemaran sungai dan laut, rusaknya ekosistem hutan, hilangnya biodiversitas, dan pengusiran masyarakat dari tanah leluhur mereka. Semua ini terjadi demi memenuhi kepentingan pasar global, bukan untuk kesejahteraan rakyat lokal.
Situasi ini menjadikan relasi antara negara, pemilik modal, dan masyarakat lokal sebagai bom waktu, konflik laten yang sewaktu-waktu bisa meledak. Ketimpangan struktural, ketidakadilan ekonomi, dan kerusakan ekologi menjadi pemantik yang terus disulut oleh kerakusan sistem kapitalisme negara.
Sehingga Marx menganalisis kondisi ini dan menyimpulkan bahwa pertentangan kelas dalam struktur ekonomi hanya menyisakan luka sosial bagi kaum proletariat. Sebagaimana diungkapkan dalam Das Kapital Volume I: “Akumulasi kekayaan pada satu kutub adalah, pada waktu yang sama, akumulasi penderitaan, kerja paksa, perbudakan, kebodohan, brutalitas, dan degradasi moral di kutub lain.”
Pada akhirnya, semua ini akan membawa penderitaan kolektif dan trauma sejarah yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
Ryan Suneth Sekretaris Umum HMI Komisariat Ekonomi Unidar Ambon
*) Konten di Sudut Opini merupakan tulisan opini pengirim yang dimuat oleh redaksi Sudut Nusantara News (SNN)