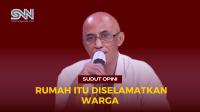Sudut Opini — Sudah menjadi budaya masyarakat kita bahwa setiap datangnya Hari Raya Idulfitri, selalu disambut dengan saling memaafkan. Ucapan seperti “mohon maaf lahir dan batin” menggema di berbagai penjuru, menjadi simbol bahwa kita ingin menghapus luka, membuka lembaran baru, dan kembali kepada fitrah. Itulah semangat yang dibawa oleh Idulfitri—sebuah kembalinya jiwa pada kesucian setelah satu bulan penuh beribadah dan bermuhasabah di bulan Ramadan.
Dalam konteks ini, bermaafan bukan sekadar basa-basi tahunan, tapi merupakan perwujudan nilai luhur Islam. Kita saling memaafkan bukan karena tidak ada kesalahan, tapi karena kita menyadari bahwa manusia tempatnya khilaf, dan memaafkan adalah jalan menuju kedamaian sosial. Allah telah terlebih dahulu memberi ampunan kepada hamba-Nya yang bertobat di bulan Ramadan, maka kita pun diajak untuk meneladani sifat tersebut dalam relasi sesama manusia.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah semarak Lebaran, masyarakat masih dihadapkan pada kenyataan pahit tentang kondisi negeri ini. Berbagai persoalan—korupsi, ketimpangan sosial, penegakan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, dan kebijakan-kebijakan yang tak berpihak pada rakyat kecil—semua itu menjadi beban kolektif yang tak kunjung usai. Dalam situasi seperti ini, wajar jika masyarakat merasa marah, kecewa, bahkan frustrasi.
Lalu, kepada siapa amarah itu diarahkan? Tak lain dan tak bukan, kepada para pemangku kebijakan: pemerintah. Mereka yang memiliki kewenangan membuat keputusan, mengatur hajat hidup orang banyak, dan bertanggung jawab atas jalannya negara. Ketika kondisi negara buruk, maka pemimpinnya pun akan mendapat sorotan. Ini adalah sesuatu yang logis dalam konteks sosial dan politik.
Pertanyaannya: apakah kita juga harus memaafkan pemerintah? Apakah kita, sebagai umat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang dan pemaafan, harus serta-merta menutup mata terhadap kesalahan-kesalahan mereka?
Sebagian orang, terutama para aktivis, menulis dan berkata dengan nada yang tegas: “Semua dimaafkan, kecuali pemerintah.” Ungkapan semacam ini tentu muncul dari kekecewaan yang mendalam. Namun jika ditelaah lebih jauh, kalimat ini bisa terkesan tidak bijak. Ia memberi kesan dendam yang berlarut-larut, bahkan seakan memosisikan diri sebagai pihak yang tidak akan pernah puas sampai kesalahan terkecil pun diadili dan dihukum.
Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi pendendam. Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang, yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya, Muhammad ﷺ, sebagai bentuk cinta-Nya kepada seluruh alam. Namun, rahmat dalam Islam bukan berarti pasrah, bukan pula berarti membiarkan kezaliman merajalela. Islam mengajarkan keseimbangan antara maaf dan keadilan, antara kasih dan kebenaran.
Memang benar, kita diajarkan untuk melawan kezaliman, melawan thaghut, dan segala bentuk kesewenang-wenangan. Namun dalam perjuangan itu, Islam menuntun kita agar tetap menjaga akhlak, menggunakan akal sehat, dan merawat hati. Rasulullah ﷺ sendiri adalah teladan dalam hal ini. Beliau mampu memaafkan musuh-musuhnya yang dulu menyakiti dan menghina, namun beliau juga tidak ragu menegakkan kebenaran dengan tegas jika kezaliman mulai melampaui batas.
Kisah Wahsyi bin Harb adalah contoh nyata. Ia adalah orang yang membunuh Hamzah, paman Nabi, dalam Perang Uhud. Setelah memeluk Islam, Wahsyi datang kepada Nabi dengan niat tulus ingin bertobat. Nabi memaafkan Wahsyi, menerima keislamannya, dan tidak pernah menghukumnya atas perbuatan masa lalu. Namun, Nabi tetap merasa berat untuk melihat wajah Wahsyi, bukan karena benci, tapi karena wajah itu mengingatkan beliau pada kehilangan yang amat mendalam.
Ini menunjukkan bahwa memaafkan tidak sama dengan melupakan. Memori tentang rasa sakit bisa tetap tinggal, dan itu manusiawi. Kita bisa memaafkan seseorang tanpa harus sepenuhnya menghapus kewaspadaan atau sikap kritis. Dalam konteks yang lebih luas, memaafkan pemerintah bukan berarti membiarkan mereka terus bertindak semena-mena. Kita tetap bisa bersikap kritis, menyuarakan kebenaran, dan menuntut perbaikan, tanpa menyimpan dendam.
Muslim yang baik bukan hanya yang pandai memaafkan, tapi juga yang mau ikut membenahi. Seperti ungkapan Patrick Geddes: “Think globally, act locally.” Berpikir secara menyeluruh namun bertindak dalam ruang lingkup sekitar. Prinsip ini juga selaras dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk aktif memperbaiki lingkungan sosialnya, dimulai dari lingkup yang paling kecil: keluarga, masyarakat, lalu bangsa.
Dalam kerangka inilah, konsep masyarakat madani atau civil society bisa tumbuh. Masyarakat yang saling menghargai, saling memaafkan, namun tidak mentolerir ketidakadilan. Masyarakat yang menjadikan Islam sebagai landasan moral dalam bernegara, bukan hanya dalam ruang-ruang ibadah tapi juga dalam praktik sosial, ekonomi, dan politik.
Akhirnya, menjadi jelas bahwa memaafkan bukan berarti membiarkan. Memaafkan adalah bentuk kemuliaan hati, sedangkan melawan ketidakadilan adalah panggilan nurani. Keduanya bisa berjalan berdampingan. Dalam setiap maaf yang kita berikan, ada harapan akan perbaikan. Dan dalam setiap kritik yang kita sampaikan, ada cinta untuk negeri.
Ahmad Yusron Chasani
Instruktur HMI Cabang Salatiga
*) Konten di Sudut Opini merupakan tulisan opini pengirim yang dimuat oleh Redaksi Sudut Nusantara News