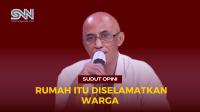Sudut Opini – Indonesia adalah negeri anugerah. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan menganugerahkan kekayaan alam yang tiada tanding. Tapi jika ada satu tempat yang bisa disebut sebagai sisa terakhir dari surga di bumi, maka Papualah tempat itu. Di ujung timur garis khatulistiwa, hamparan hutan tropis yang lebat masih berdiri, lautannya kaya akan terumbu karang yang memukau, dan budaya masyarakat adatnya begitu luhur.
Papua bukan sekadar lanskap eksotis dalam kartu pos pariwisata. Ia adalah nadi kehidupan bagi lebih dari 250 suku bangsa, penjaga hutan hujan tropis terakhir Indonesia, serta rumah bagi keanekaragaman hayati yang tak ditemukan di tempat lain di muka bumi. Namun kini, surga ini sedang di ujung tanduk kerusakannya.
Dibungkus narasi manis soal pembangunan nasional dan transisi energi, Papua sedang dilumuri oleh tinta hitam nikel. Nikel, logam yang disebut-sebut sebagai komponen kunci dalam revolusi hijau global, justru menjadi simbol luka dan kehancuran di tanah Papua. Ia hadir bukan sebagai harapan, tetapi sebagai ancaman yang tak kasat mata yakni merampas ruang hidup, menghancurkan bentang alam, dan menyingkirkan eksistensi masyarakat adat yang selama ini justru menjaga alam dengan segenap jiwanya.
Menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), hingga tahun 2023, terdapat lebih dari 50 konsesi tambang nikel aktif di Papua Barat dan Papua. Ironisnya, sebagian besar konsesi ini berada di atas tanah adat dan kawasan penting secara ekologis seperti Pegunungan Cycloop di Jayapura dan Cagar Alam Wasur di Merauke. Fakta lebih menyakitkan lagi ketika melihat data bahwa hanya sekitar 8% wilayah Papua yang telah dipetakan secara sah sebagai tanah ulayat atau tanah adat. Artinya, mayoritas lahan adat Papua berada dalam status abu-abu yang mudah diklaim dan dieksploitasi tanpa persetujuan yang jelas dari masyarakat pemiliknya.
Di atas kertas, nikel dijual sebagai “logam hijau” kunci transisi energi dunia menuju masa depan bebas emisi. Tapi di Papua, logam ini justru berdarah merah. Di Teluk Bintuni, sungai-sungai yang dulu jernih kini coklat pekat oleh limbah tambang. Di Fakfak, kebun sagu yang menjadi sumber pangan utama masyarakat adat telah mengering, rusak oleh perluasan lahan tambang. Dan di Raja Ampat, tempat yang dijuluki sebagai laboratorium alam dunia karena keanekaragaman lautnya, bayang-bayang pembangunan smelter nikel mulai menodai cakrawala birunya.
Riset WALHI Papua menyebut bahwa sekitar 70% konflik agraria di Papua saat ini terkait dengan ekspansi proyek pertambangan dan perkebunan. Yang paling menderita dari konflik ini adalah perempuan adat. Mereka kehilangan akses terhadap sumber air, lahan kebun, dan tempat-tempat sakral. Padahal mereka adalah tulang punggung kehidupan komunitas adat penjaga pangan, penyembuh, dan pemelihara harmoni alam.
“Kami tidak pernah setuju tanah kami ditambang,” kata Mama Yulce, perempuan adat dari Sorong Selatan. “Tapi mereka datang dengan dokumen, tentara, dan janji kosong.”
Kisah Mama Yulce bukan satu-satunya. Ia adalah satu suara dari sekian banyak yang telah berteriak, tapi sering kali diabaikan. Dalam banyak kasus, aparat keamanan bahkan dilibatkan untuk mengawal investasi dan memukul mundur penolakan warga.
Papua bukan tanah kosong. Ini bukan halaman belakang negeri yang bisa diacak-acak seenaknya atas nama pertumbuhan ekonomi. Ini adalah tanah dengan sejarah, identitas, dan nyawa. Tapi dalam bayang-bayang proyek strategis nasional, suara rakyat Papua kerap hanya dianggap sebagai gangguan. Istilah “pembangunan” kehilangan maknanya dan berubah menjadi “perampasan”. Investasi menjadi sinonim dari intimidasi.
Kita harus bertanya, apakah kita benar-benar butuh nikel yang ditambang dari air mata anak-anak Papua? Apakah kendaraan listrik di kota besar pantas dibayar dengan kerusakan ekologis dan penderitaan masyarakat adat? Apakah kita rela menyelamatkan iklim global sambil menghancurkan ekosistem lokal yang tak tergantikan?
Ada ironi besar dalam ambisi dunia menuju energi hijau. Transisi yang seharusnya menyelamatkan bumi justru menciptakan kolonialisme baru menyasar wilayah-wilayah pinggiran seperti Papua yang dianggap tak punya suara. Padahal justru masyarakat adatlah yang selama ribuan tahun hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya.
“Kami menjaga hutan bukan karena kami dibayar. Tapi karena kami hidup dari situ. Itu darah kami.” ucap Yulianus Pigai, Ketua Dewan Adat Papua.
Pernyataan itu adalah pengingat bahwa pelindung terbaik alam bukanlah sistem hukum formal atau korporasi berlabel hijau, melainkan orang-orang yang selama ini dianggap terbelakang. Padahal justru mereka yang paling maju dalam filosofi keberlanjutan.
Sudah saatnya kita berhenti menutup mata. Surga kecil bernama Papua tak boleh dibayar dengan kematian alam dan hilangnya jati diri persatuan Indonesia. Ini bukan soal pembangunan atau pertumbuhan ekonomi semata. Ini soal pilihan moral dan keadilan antargenerasi. Karena saat satu surga hancur, seluruh dunia ikut kehilangan. Dan kita semua akan ikut menanggung akibatnya.
Dani Febri Fungsionaris Badko HMI Jawa Timur
*) Konten di Sudut Opini merupakan tulisan opini pengirim yang dimuat oleh redaksi Sudut Nusantara News (SNN)